Gelar Pahlawan Nasional
Rumah Amir Biki Korban Tanjung Priok 1984 Kini Jadi TPQ: Luka Era Soeharto Belum Sembuh
TPQ ini dulunya rumah korban Tanjung Priok 1984. Anak-anak mengaji di tengah jejak darah, mimpi kematian, dan luka sejarah yang belum sembuh.
Ringkasan Berita:
- Lia Biki bermimpi ayahnya tewas sebelum kabar resmi datang tengah malam.
- Rumah korban tragedi berdarah kini jadi tempat anak-anak mengaji setiap sore.
- Soeharto dianugerahi gelar pahlawan, keluarga korban masih menanti keadilan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Setiap sore selepas salat ashar, anak-anak kecil berdatangan ke sebuah rumah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka membawa Al-Qur’an, duduk bersila di atas karpet, dan mulai belajar mengaji.
Rumah itu bukan sembarang tempat.
Di balik tembok hijau dan papan bertuliskan “TPQ Tunas Irfan dan Perpustakaan Dahlia”, tersimpan jejak sejarah kelam: rumah ini adalah kediaman Amir Biki, tokoh masyarakat yang tewas dalam peristiwa kerusuhan Tanjung Priok pada 12 September 1984, di era pemerintahan Presiden Soeharto.
Kini, rumah itu diurus oleh dua anak Amir Biki, Lilah Khodijah dan Nur Dahlia Biki, atau Lia Diki. Bersama warga sekitar, mereka mengubah ruang duka menjadi ruang belajar.
“TPQ-nya setiap hari bada ashar. Anak-anak sama ibu-ibu belajar Quran. Kalau malam Jumat khusus majelis ta'lim kaum ibu. Ini permintaan dari almarhumah mamah,” kata Lia saat ditemui Tribunnews.com di lokasi, Selasa (11/11/2025).
Di dalam rumah, tak ada ruang tamu seperti biasanya. Sofa letter L menempel di dinding, rak buku anak-anak berdiri di sudut, dan karpet besar terbentang untuk tempat mengaji. Di tembok, terpajang foto hitam-putih Amir Biki dan istrinya, Hj. Dewi Wardah.
“Itu yang kami sayangkan. Kami nggak punya foto almarhum ayah. Jadi kebanyakan fotonya dilukis,” ujar Lia.
Lekar cokelat untuk meja Al-Qur’an telah disiapkan. Lia, yang menguasai ilmu agama, turun langsung mengajar anak-anak.
Dulu, rumah ini juga menjadi tempat praktik sang ibu yang dikenal sebagai bidan di kawasan Priok.
“Di sini juga jadi tempat merawat almarhumah mamah waktu sakit. Di dalam itu udah kayak rumah sakit, peralatan medis banyak,” kenang Lia.
Baca juga: Mengintip Rumah Cendana: Tempat Soeharto Dulu Berkumpul, Kini Ditinggal Anak-anaknya
Luka yang Belum Sembuh
Kerusuhan Tanjung Priok 1984 menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah politik Indonesia, khususnya di era pemerintahan Presiden Soeharto.
Menurut catatan Komnas HAM yang dimuat dalam Kontras.org, sedikitnya 79 orang menjadi korban. Sebanyak 55 orang terluka dan 23 lainnya tewas dalam bentrokan antara warga sipil dan aparat keamanan dari unsur militer. Namun, hingga kini angka pasti korban masih simpang siur.
Ketegangan bermula pada 7 September 1984, ketika Sersan Hermanu mendatangi Musala Assa’addah di Koja, Tanjung Priok, dan meminta warga mencopot brosur serta spanduk berisi kritik terhadap pemerintah Orde Baru.
Dikutip dari Kompas.id, Hermanu kembali ke musala pada 8 September dan masih menemukan pamflet-pamflet tersebut. Ia pun marah, mengacungkan pistol ke arah warga, dan masuk ke podium musala tanpa melepas sepatu larsnya. Tindakan itu memicu kemarahan masyarakat yang menuntut permintaan maaf.
Pada 10 September, pengurus musala Syarifuddin Rambe dan Ahmad Sahi berusaha menyelesaikan konflik secara damai.
Hermanu datang bersama Sertu Rahmad dan bersedia berdialog, namun menolak meminta maaf dengan alasan sebagai petugas keamanan.
Ketegangan meningkat ketika warga yang mengetahui keberadaan Hermanu mendatangi lokasi. Dalam situasi yang semakin kacau, sepeda motor milik Hermanu dibakar, dan aparat Kodim 0502 Jakarta Utara menangkap empat orang: dua pengurus musala dan dua warga.
Dua hari kemudian, pada 12 September 1984, Amir Biki—pimpinan Forum Studi dan Komunikasi 66—bersama warga mendatangi Kodim untuk meminta pembebasan empat orang yang ditahan. Ia dikenal sebagai tokoh multietnis yang dipercaya masyarakat Tanjung Priok.
“Kalau ada masalah suku A dengan suku B, datangnya ke sini. Jadi, memang salah satu tokoh di Tanjung Priok,” kata Lia, putri Amir Biki.
Namun, permintaan itu tidak ditanggapi.
Massa yang berjumlah sekitar 1.500 orang kemudian bergerak menuju Polres Jakarta Utara, namun diadang aparat militer bersenjata lengkap.
Menurut keterangan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban saat itu, Jenderal LB Moerdani, terdapat provokator di antara demonstran yang membawa senjata tajam dan bensin. Aparat mengklaim telah memberi tembakan peringatan, namun tidak direspons. Bentrokan pun pecah. Aparat menghujani massa dengan peluru sebagai langkah terakhir. Korban pun berjatuhan.
Komnas HAM mencatat sekitar 160 orang ditangkap tanpa prosedur hukum. Mereka ditahan di sejumlah fasilitas militer seperti Laksusda Jaya, Mapomdam Guntur, dan RTM Cimanggis. Sementara korban luka dan tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Penanganan peristiwa ini dilakukan oleh unsur militer di bawah struktur ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang saat itu mencakup TNI dan Polri.
Bagi keluarga korban, termasuk Lia Biki yang saat itu baru berusia enam tahun, peristiwa tersebut meninggalkan luka mendalam yang belum sembuh hingga kini.
Baca juga: VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Alissa Wahid: Tujuan Utama Kami Gus Dur Pahlawan di Hati Rakyat
Mimpi dan Kabar Duka
Lia Biki masih kecil ketika peristiwa itu terjadi.
Ia terbangun dari tidur dengan perasaan gelisah.
“Malam itu saya memang yang kemudian dimimpin,” katanya.
“Bangun tidur tuh teriak-teriak, ‘Bapak nggak ada, Bapak meninggal,’ kayak gitu Mama.”
Tak lama, sang ibu menerima kabar dari Wakil Gubernur DKI saat itu, Edi Nalapraya, bahwa Amir Biki telah meninggal dunia.
“Kalau di teleponnya bahasanya seperti apa saya juga enggak paham, tapi memang malam itu kan kejadiannya tengah malam ya,” ujar Lia.
Sejak saat itu, rumah keluarga Biki menjadi saksi bisu perjuangan dan kehilangan.
Kini, Lia bersama 13 keluarga korban yang tersisa masih mencari keadilan atas kekerasan aparat di era Soeharto.
“Kami masih terus berjuang,” katanya.
Pahlawan di Tengah Luka Sejarah

Pada Senin, 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Jakarta.
Penganugerahan itu dilakukan sekitar satu tahun setelah Prabowo resmi menjabat sebagai presiden, menjadikannya momen simbolik dalam lanskap politik nasional.
Sebagai mantan menantu Presiden Soeharto, Prabowo menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada masing-masing keluarga, termasuk keluarga Soeharto yang diwakili oleh dua anaknya: Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto.
Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas kontribusinya di bidang perjuangan bersenjata dan politik. Ia dikenal sebagai tokoh sentral Orde Baru yang memimpin Indonesia selama 32 tahun, dari 1966 hingga 1998. Di bawah pemerintahannya, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas, namun juga diwarnai dengan pembungkaman oposisi, dominasi militer dalam kehidupan sipil, dan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Peristiwa Tanjung Priok 1984 menjadi salah satu titik kelam dalam era kekuasaannya.
Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.
“Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” bunyi kutipan Keppres tersebut.
Selain Soeharto, sembilan tokoh lain juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, termasuk KH Abdurrahman Wahid dan Marsinah.
Di tengah penghargaan itu, keluarga korban Tanjung Priok 1984 masih menyimpan luka yang belum sembuh.
Bagi Lia Biki dan 13 keluarga korban yang tersisa, pengakuan terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional menyisakan pertanyaan sejarah yang belum tuntas.
Rumah Amir Biki, yang kini menjadi TPQ dan ruang belajar, tetap menyimpan jejak trauma dan perjuangan.
Di balik lantunan ayat suci dan tawa anak-anak, sejarah kelam itu tetap hidup—menunggu keadilan yang belum datang.



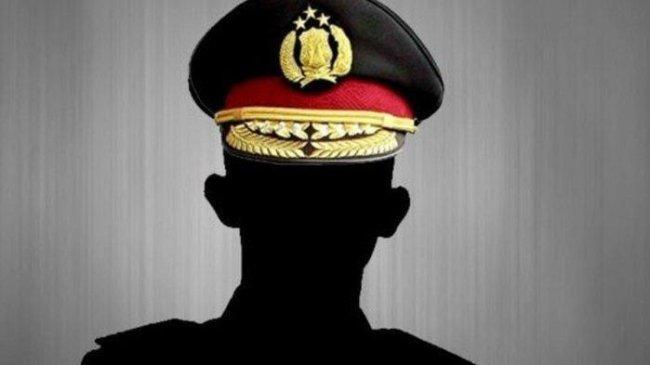
![[FULL] Ancaman Pidana Roy Cs Kasus Ijazah Jokowi, Pakar Peringatkan Tak Ditahan Belum Tentu Ringan](https://img.youtube.com/vi/ejyr-iWQfr4/mqdefault.jpg)
















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.