Semakin Dilarang, Semakin Menyala: Fenomena Sukatani dan Streisand Effect di Era Digital
Polemik yang menimpa Sukatani menjadi contoh nyata Streisand effect yang menyebutkan bahwa konten yang diblokir cenderung menarik lebih besar
TRIBUNNEWS.COM - Mengapa sesuatu yang dilarang justru semakin menarik? Dalam era digital, upaya untuk menyensor informasi sering kali menjadi bumerang. Mengutip International Journal of Communication yang berjudul "The Streisand Effect and Censorship Backfire" yang menyebutkan bahwa konten yang diblokir atau dihapus cenderung menarik perhatian lebih besar karena dianggap sebagai sesuatu yang "terlarang" atau "eksklusif." Fenomena ini dikenal sebagai Streisand Effect — semakin ditekan, semakin meluas.
Di Indonesia, kasus band punk asal Purbalingga, Sukatani, menjadi bukti nyata. Lagu mereka, “Bayar Bayar Bayar,” yang mengkritik pungutan liar oleh oknum aparat, semakin viral setelah ada upaya untuk menghapusnya dari platform digital. Alih-alih meredam, larangan ini justru memicu rasa penasaran dan solidaritas publik. Semakin dilarang, semakin banyak orang yang mencari, mendengar, dan menyebarkannya.
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa di era internet, sensor bukanlah solusi, justru bisa menjadi bahan bakar untuk penyebaran informasi. Bahkan tagar #kamibersamasukatani sempat menjadi trending topic di aplikasi X beberapa hari lalu, menyusul dugaan intimidasi yang dialami saat personel Sukatani mengunggah video permintaan maaf yang ditujukan ke institusi Polri dan Kapolri.
Baca juga: Pengamat: Kapolda Jateng Irjen Ribut Harus Diperiksa soal Dugaan Intimidasi pada Band Sukatani
Asal-usul Streisand Effect
Fenomena Streisand Effect pertama kali muncul pada tahun 2003, ketika Barbra Streisand berupaya menghapus foto rumahnya dari arsip dokumentasi erosi pantai di California. Sebelum ada kontroversi, hanya segelintir orang yang mengetahui keberadaan foto tersebut. Namun, setelah Streisand menggugat fotografernya, perhatian publik justru melonjak. Dalam waktu singkat, foto yang sebelumnya nyaris tak dikenal akhirnya dilihat oleh jutaan orang.
Dari sudut pandang psikologi, fenomena ini erat kaitannya dengan teori reaktansi psikologis yang dikembangkan oleh Jack Brehm pada 1966. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan kebebasan mereka. Ketika akses terhadap sesuatu dibatasi atau dilarang, keinginan untuk mendapatkannya justru semakin besar.
Singkatnya, semakin sesuatu dianggap terlarang, semakin besar daya tariknya. Itulah sebabnya, di era digital, sensor sering kali menjadi bumerang—bukan meredam, tapi justru mempercepat penyebaran informasi.
Beberapa faktor utama yang memperkuat dampaknya antara lain:
- Rasa Ingin Tahu – Informasi yang dilarang menciptakan kesan eksklusivitas, membuat orang semakin penasaran.
- Efek Bumerang – Sensor sering kali dipersepsikan sebagai tindakan represif, memicu solidaritas publik dan aktivisme digital.
- Akses Informasi di Era Digital – Dengan internet, penghapusan informasi hampir mustahil dilakukan. Upaya menghapus sesuatu sering kali mempercepat penyebarannya.
- Dinamika Media Sosial – Algoritma media sosial memperkuat konten yang mendapat interaksi tinggi, sehingga isu yang diblokir justru semakin viral.
Hasilnya? Larangan malah jadi “iklan gratis.” Itulah sebabnya upaya sensor di era digital sering kali berakhir dengan efek sebaliknya: bukan mengubur informasi, tapi justru mengangkatnya ke permukaan.
Streisand Effect di Kasus Lain
Fenomena Streisand Effect tidak hanya terjadi pada kasus Sukatani atau Barbra Streisand sendiri, tetapi juga terlihat dalam berbagai kasus lainnya, baik di tingkat internasional maupun nasional.
Salah satu contoh paling mencolok adalah kasus Edward Snowden pada tahun 2013. Pemerintah Amerika Serikat berusaha membatasi akses terhadap bocoran dokumen NSA yang diungkap olehnya. Namun, alih-alih meredam informasi, langkah ini justru membuat dokumen tersebut semakin tersebar luas dan menarik perhatian publik secara global.
Di Indonesia, fenomena ini tampak dalam kontroversi film dokumenter The Act of Killing (2012), yang membahas tragedi pembantaian 1965-1966. Larangan pemutarannya tidak menghentikan masyarakat untuk menonton. Justru sebaliknya, film ini semakin banyak dibahas, didistribusikan secara digital, dan menarik perhatian dunia.
Hal serupa juga terjadi dalam kasus pelarangan beberapa buku sejarah di Indonesia. Buku-buku yang dilarang pemerintah malah menjadi incaran banyak orang. Versi digitalnya diperbanyak, dan justru semakin banyak yang membacanya karena rasa penasaran.
Fenomena ini membuktikan bahwa di era digital, kontrol informasi menjadi semakin sulit. Alih-alih menghilangkan suatu isu, sensor justru bisa menjadi katalis penyebarannya. Transparansi dan komunikasi yang efektif jauh lebih penting daripada sekadar mencoba menutup akses terhadap informasi.
Penulis: Vincentius Haru | Editor: Muh. Fitrah
| Harta Kekayaan Akhmad Wiyagus, Eks Kabaintelkam Polri yang Kini Jabat Wakil Menteri Dalam Negeri |

|
|---|
| Di Balik Seragam Brimob, Bharatu Yudha Sukses Tekuni Beternak Kambing dan Berdayakan Warga |

|
|---|
| Polda NTT Gelar Bakti Kesehatan, Puluhan Warga Kampung Pasat Dapat Layanan Gratis |

|
|---|
| Terbilang Rendah, Kinerja HAM Polri Cuma Dapat Skor 57,8 |

|
|---|
| Lemkapi Sebut Pihak yang Mengusulkan Polri di Bawah Kementerian Tak Paham Sejarah |

|
|---|






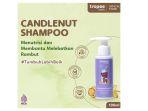


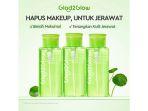






Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.